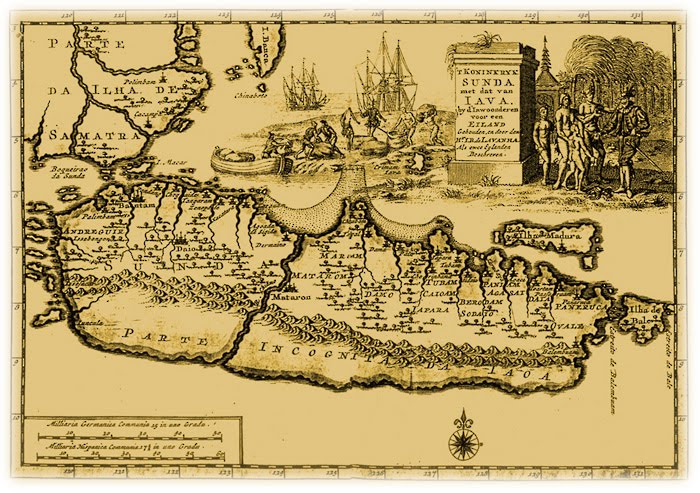Melawan Lupa: Perubahan Arsitektur Sunda
Setelah Terpapar Wabah Sampar (Pes)
oleh:
Nandang Rusnandar
(BPNB Jabar)
Kampung Papandak (Wanaraja Garut), sekitar tahun 1910 -1930 merupakan sebuah kampung yang berarsitektur sangat indah dengan atap julang ngapak, dan bermaterialkan bahan yang harmoni dengan alam yaitu bambu, kayu, alang-alang atau ijuk. Ch. E. Stehn mengabadikan hal itu dalam bukunya Gids voor Bergtochten op Java (1930); dan fotografer Thilly Weissenborn pernah mengabadikan bangunan-bangunan khas di Papandak dalam buku Vastgelegd voor later (1917). Saking istimewanya daerah Papandak, pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1919, menetapkannya sebagai monumen alam (“Aanwijzing van terreinen als natuurmonumenten”).

Pada 6 November 1929 kebakaran besar terjadi, menyebabkan terbakar habis 121 rumah, tiga tajug (musala), dan leuit (lumbung). Kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai 30 sampai 40 ribu gulden. Penyebabnya seorang kakek, dalam rangka menyambut kelahiran cucunya, menyulut lodong, sehingga api dari bedil bambu tersebut merambat ke rumah-rumah yang bertiangkan kayu, berdinding bambu, dan beratapkan jerami. Kebakaran tersebut diberitakan oleh Kantor berita Aneta dan koran-koran di Hindia Belanda, bahkan di Belanda sendiri antara 6-8 November 1929 diberitakan dengan istilah “Brand in het Garoetsche”, “Groote brand” dan “Zware Brand bij Garoet”. Saat kebakaran terjadi, wabah sampar sedang merajalela, pada tahun itu meminta korban sebanyak 1.812 orang dan pada tahun 1933 tercatat yang meninggal sebanyak 15.188 orang, pada 1934 meningkat 25% menjadi 20.569 orang.
Upaya pencegahan merebaknya wabah Sampar, pemerintah kolonial mengubah bentuk arsitektur rumah dengan setengah tembok (duduk jandela). Ada pula yang menyayangkannya dari sisi budaya. Hal ini, misalnya, dapat dibaca dari tulisan Aboebakar van Bintoro, “Architectuur Oerang Soenda Sanggeusna Kataradjang koe Pest” (dalam koran Sipatahoenan edisi 19 April 1934). (“matak sedih katendjona,.. Malah ngerik saenjana /…/ Noe tadina imahna make kolong. Model hateupna roepa-roepa! (Boehna kaboedajaan A.v.B). Nja soeroep, nja sari katendjona. Boh di toendjangeun pasir atawa dina lamping. Soeroep imah pagoenoengan Soenda! Njerep kana rasa kasoendaan. Da poegoeh diadegkeunana teh make rasa kasoendaan, make kaboedajaan Soenda!” (Asalnya rumah berkolong. Atapnya bermacam-macam! (Hasil kebudayaan AvB). Sesuai dan elok terlihat. Baik yang berada di kaki bukit maupun di lembah. Betapa eloknya rumah pegunungan di Tatar Sunda! Hanyut dalam rasa kesundaan. Karena memang didirikan atas dasar rasa kesundaan, memakai kebudayaan Sunda! Setelah adanya woningverbetering, Aboebakar menilai, “Lemboer oerang Soenda tingroenggoenoek djiga pisan bedeng-bedeng kontrakan!”
Disarikan dari tulisan asli berjudul :
Arsitektur Sunda Setelah Wabah Sampar,
Sumber :
URL https://m.ayobandung.com/read/2020/04/16/86210/arsitektur-sunda-setelah-wabah-sampar.