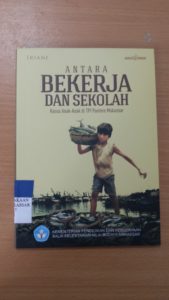PENDIDIKAN KARAKTER DALAM LINGKUNGAN KELUARGA PADA MASYARAKAT MUNA DI SULAWESI TENGGARA
Abdul Asis
Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan
Jalan Sultan Alauddin / Tala Salapang Km. 7 Makassar, 90221
Telepon (0411) 885119, 883748, Faksimile (0411) 865166
Pos-el: asisabdul72@gmail.com
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi akan keberadaan budaya-budaya lokal yang dimiliki oleh setiap suku bangsa di Indonesia, tidak terkecuali suku Muna di Sulawesi Tenggara yang hingga saat ini belum optimal di dalam upaya membangun karakter anak, bahkan setiap saat kita saksikan berbagai macam tindakan masyarakat yang berakibat pada kehancuran yakni menurunnya perilaku sopan santun, menurunnya perilaku kejujuran, menurunnya rasa kebersamaan, dan menurunnya rasa gotong royong di antara anggota masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memperoleh gambaran secara deskriptif tentang pendidikan karakter dalam lingkungan keluarga pada masyarakat Muna. Pendekatan penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi literatur. Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi, display dan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukan bahwa wujud pendidikan karakter bukan hanya melalui pendidikan sekolah (formal) tempat pendidikan karakter bisa di dapatkan dalam lingkungan keluarga, yang dimulai dipendidikan saat perkembangan janin dalam rahim ibu hingga mereka telah menemukan pasangan hidup. Budaya-budaya lokal tersebut sebagai wadah dalam transformasi nilai-nilai budaya.
Kata Kunci: pendidikan, karakter, lingkungan keluarga.
PENDAHULUAN
Pendidikan diawali saat bayi itu dilahirkan dan biasanya berlangsung seumur hidup. Namun biasa pula pendidikan berawal sejak bayi masih dalam kandungan seperti ibunya sering memainkan alat musik, menyanyi dan membaca ketika sedang mengandung dengan harapan mengajar bayi mereka sebelum kelahiran. Bagi sebagian orang, pengalaman hidup sehari-hari lebih berarti daripada pendidikan formal. seperti kata Mark Twain, “Saya tidak pernah membiarkan sekolah mengganggu pendidikan saya.” (Chintya, 2015). Anggota keluarga mempunyai peran pengajaran yang amat mendalam, sering kali lebih mendalam dari yang disadari mereka, walaupun pengajaran anggota keluarga berjalan secara tidak resmi.
Menurut Horton dan Hunt (1993), lembaga pendidikan berkaitan dengan fungsi yang nyata (manifest) sebagai berikut: a) Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. b) Mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. c) Melestarikan kebudayaan. d) Menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi.
Pendidikan sangat penting kedudukannya sebagai sentral dalam pembangunan, karena berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan merupakan suatu proses transformasi nilai-nilai budaya sebagai kegiatan pewarisan budaya dari suatu generasi ke generasi yang lain. Nilai-nilai budaya tersebut mengalami proses transformasi dari generasi terdahulu sampai pada generasi sekarang dan generasi yang akan datang.
Pendidikan karakter adalah sebuah upaya untuk membimbing perilaku menusia menuju standar-standar baku. Upaya ini memberikan jalan untuk menghargai persepsi dan nilai pribadi yang ditampilkan di sekolah. Fokus pendidikan karakter adalah pada tujuan-tujuan etika, tetapi praktiknya meliputi penguatan kecakapan-kecakapan yang penting yang mencakup perkembangan sosial anak.
Seseorang dapat dikatakan berkarakter jika telah berhasil menyerap nilai dan keyakinan yang dikehendaki masyarakat serta digunakan sebagai kekuatan moral dalam hidupnya. Jadi suatu bangsa dapat dikatakan berkarakter jika bangsa itu memiliki nilai dan keyakinan yang dilandasi tujuan dari bangsa itu sendiri. Ciri-ciri dasar pendidikan karakter menurut Foester (dalam Abdullah, 1998:37) terdiri atas empat, yaitu: 1) Keteraturan interior di mana setiap tindakan diukur berdasarkan hierarki. Nilai menjadi pedoman normatif dalam setiap tindakan. 2) Koheransi yang memberi keberanian membuat seseorang teguh pada prinsip, dan tidak mudah terombang-ambing pada situasi baru atau takut resiko. 3) Otonomi, di mana seseorang menginternalisasikan aturan dari luar sampai menjadi nilai-nilai bagi pribadi. 4) Keteguhan dan kesetiaan.
Pada dasarnya budaya memiliki nilai-nilai yang senantiasa diwariskan, ditafsirkan dan dilaksanakan seiring dengan proses perubahan sosial kemasyarakatan. Pelaksanaan nilai-nilai budaya merupakan bukti legitimasi masyarakat terhadap budaya. Eksistensi budaya dan keragaman nilai-nilai luhur kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan sarana dalam membangun karakter warga negara, baik yang berhubungan dengan karakter privat maupun karakter publik.
Namun seiring perkembangan zaman, eksistensi nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sampai saat ini belum optimal dalam upaya membangun karakter warganya, bahkan setiap saat kita menyaksikan berbagai macam tindakan masyarakat yang berakibat pada kehancuran suatu bangsa yakni menurunnya perilaku sopan santun, menurunnya perilaku kejujuran, menurunnya rasa kebersamaan, dan menurunnya rasa gotong royong di antara anggota masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut Lickona (1992:32) membagi sepuluh tanda dari perilaku manusia yang menunjukan arah kehancuran suatu bangsa yaitu: (1) meningkatnya kekerasan di kalangan remaja; (2) ketidakjujuran yang membudaya; (3) semakin tingginya rasa tidak hormat kepada orang tua, guru dan figur pemimpin; (4) pengaruh peer group terhadap tindakan kekerasan; (5) meningkatnya kecurigaan dan kebencian, (6) penggunaan bahasa yang memburuk; (7) penurunan etos kerja; (8) menurunnya rasa tanggungjawab individu dan warga negara; (9) meningginya perilaku merusak diri; dan (10) semakin kaburnya pedoman moral.
Pembangunan karakter bangsa melalui nilai-nilai budaya lokal sangatlah dibutuhkan dan dapat ditempuh dengan cara mentransformasi nilai-nilai budaya lokal sebagai salah satu sarana untuk membangun karakter bangsa. Pentingnya transformasi nilai-nilai budaya lokal sebagai salah satu sarana untuk membangun karakter bangsa adalah sebagai berikut: (1) Secara filosofis pembangunan karakter bangsa merupakan sebuah kebutuhan asasi dalam proses berbangsa karena hanya bangsa yang memiliki karakter dan jati diri yang kuat yang akan eksis; (2) Secara ideologis, pembangunan karakter merupakan upaya mengejewantahkan ideologi pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara normatif, pembangunan karakter bangsa merupakan wujud nyata langkah mencapai tujuan negara; (3) Secara historis, pembangunan karakter bangsa merupakan sebuah dinamika inti proses kebangsaan yang terjadi tanpa henti dalam kurun sejarah, baik pada zaman penjajah, maupan pada zaman kemerdekaan; (4) Secara sosiokultural, pembangunan karakter bangsa merupakan suatu keharusan dari suatu bangsa yang multikultural (Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025:1).
Berdasarkan hal tersebut di atas, pembangunan karakter bangsa melibatkan berbagai pihak baik keluarga, lingkungan sekolah, serta masyarakat luas. Pembangunan karakter bangsa tidak akan berhasil selama pihak-pihak yang berkompeten untuk menunjang pembangunan karakter tersebut tidak saling bekerja sama. Oleh karena itu, pembangunan karakter bangsa perlu dilakukan di luar sekolah atau pada masyarakat secara umum sesuai dengan kearifan budaya lokal masing-masing. Hal yang sama disampaikan oleh Eddy (2009:5) bahwa “pelestarian kebudayaan daerah dan pengembangan kebudayaan nasional melalui pendidikan baik pendidikan formal maupun nonformal, dengan mengaktifkan kembali segenap wadah dan kegiatan pendidikan”.
Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini telah mempercepat berubahnya nilai-nilai sosial budaya yang membawa dampak positif dan negatif terhadap pertumbuhan bangsa kita terutama dalam keluarga dan lingkungan masyarakat. Dampak positifnya adalah bertambahnya kecepatan dan peningkatan cara berpikir dalam berbagai bidang dan terjadinya perubahan pola hidup yang lebih efisien dan pragmatis, sedangkan dampak negatifnya masyarakat mengalami kesulitan dalam memahami dan merencanakan perkembangan yang begitu cepat di berbagai bidang tersebut, terjadinya degradasi moral bangsa yang sulit terkendali, sehingga terjadi benturan dengan nilai-nilai luhur bangsa kita.
Kondisi bangsa kita saat ini tidak dapat menghindar dengan pengaruh globalisasi, informasi dan transparansi, mereka hanya dapat berupaya mengimbangi kemajuan atau perkembangan gaya hidup akibat kemajuan teknologi tersebut. Tidak terkecuali pada masyarakat Muna di Sulawesi Tenggara tidak terlepas dari penetrasi budaya akibat pengaruh teknologi yang serba digital yang turut mempengaruhi karakter manusia dan tatanan budaya masyarakatnya. Masyarakat suku Muna dikenal kaya akan tradisi-tradisi lokal yang berkaitan langsung dengan nilai-nilai pendidikan yang sifatnya informal, yang dapat mengimbangi kemajuan teknologi globalisasi informasi sebagai rujukan dalam pembentukan karakter (caracter building) karena banyak mengandung nilai-nilai pendidikan. Nilai-nilai pendidikan seperti itulah yang perlu dikembangkan dalam kemasan moderen dan mudah dipahami.
Melalui pranata-pranata pendidikan yang sifatnya informal dalam lingkungan keluarga merupakan salah satu sarana untuk membangun karakter bangsa melalui transformasi nilai-nilai budaya lokal. Tulisan ini akan memaparkan pranata-pranata pendidikan dalam lingkungan keluarga pada masyarakat Muna yang disesuaikan dengan perkembangan fisik dan kejiwaan anak, dimulai dari: 1) pendidikan perkembangan janin dalam kandungan, 2) pendidikan pada saat kelahiran, 3) pendidikan pada saat tumbuh gigi, 4) pendidikan pada saat penanggalan gigi pertama, 5) pendidikan pada saat mimpi basah pertama, 6) pendidikan pada saat datang haid pertama dan pendidikan pada saat pertumbuhan tinggi badan maksima, 7) pendidikan pada saat telah menemukan pasangan hidupnya.
Pranata-pranata pendidikan seperti di atas tidak mempunyai kurikulum tersendiri yang menghendaki jenjang dan waktu, tidak menghasilkan penghargaan atau tanda kehormatan dan profesionalisme, akan tetapi pendidikan ini lebih mengarah pada upaya pembentukan karakter manusia sejak masih dalam kandungan hingga lahir sampai menjadi manusia dewasa.
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan informal dalam keluarga sangatlah penting. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan kajian tentang pendidikan karakter dalam lingkungan keluarga pada masyarakat Muna di Sulawesi Tenggara.
Adapun yang menjadi rumusan permasalahan dalam kajian ini adalah bagaimana wujud pendidikan karakter dalam lingkungan keluarga pada masyarakat Muna, dimulai saat perkembangan janin dalam rahim ibu hingga mereka telah menemukan pasangan hidup sampai membina hubungan rumah tangga. Sedangkan menjadi tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui wujud pendidikan karakter dalam lingkungan keluarga pada masyarakat Muna yang dimulai saat perkembangan janin dalam rahim ibu hingga mereka telah menemukan pasangan hidup sampai membina hubungan rumah tangga.
Tinjauan pustaka merupakan bagian dari penyusunan sebuah karya tulis ilmiah di mana di dalamnya akan diungkapkan pemikiran serta teori-teori yang akan dijadikan landasan. Untuk teori yang disajikan pada tinjauan pustaka menyajikan hubungan antara beberapa konsep yang digunakan untuk menjelaskan penelitian yang dilakukan.
Pengertian pendidikan menurut Ahmad D. Marimba adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Sedangkan Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya (Binti Maunah, 2009:3-4). Dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha yang sadar, teratur dan sitematis di dalam memberikan bimbingan atau bantuan kepada orang lain (anak) yang sedang berproses menuju kedewasaaan.
Sedangkan karakter berasal dari bahasa latin “kharakter” “kharsein”, ”kharax” dalam bahasa Inggris: ”character” dan dalam bahasa Indonesia “karakter‟ dalam bahasa Yunani character dan charassein yang artinya membuat tajam, membuat dalam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh Poerwardarminta, karakter diartikan sebagai tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Nama dari jumlah seluruh ciri pribadi yang meliputi hal-hal seperti prilaku, kebiasaan, kesukaan, ketidaksukaan, kemampuan, kecenderungan, potensi, nilai-nilai, dan pola-pola pikiran (Majid dan Andayani, 2011:11).
Menurut Lickona karakter terbagi atas beberapa bagian yang tercakup di dalamnya, seperti di bawah ini:
“Character so conceived has three parts: moral knowing, moral feeling, and moral behavior. Good character consists of knowing the good, desiring the good, and doing the good, habits of the mind, habits of the heart, and habits of action. All three are necessary for leading a moral life, all three make up moral maturity. When we think about the kind of character we want for our children, it’s clear that we want them to be able to judge what is right, care deeply about what is right, and the do what they believe to be right, even in the face of pressure from without and temptation from within” (Lickona, 1991:51).
Berdasarkan pendapat Lickona di atas dijelaskan bahwa karakter terdiri atas tiga korelasi yakni moral knowing, moral feeling, dan moral behavior. Karakter sendiri terdiri atas, antara lain: mengetahui hal-hal baik, memiliki keinginan untuk berbuat baik, dan melaksanakan hal yang baik tadi berdasarkan pemikiran, dan perasaan, apakah hal tersebut baik untuk dilakukan atau tidak, kemudian dikerjakan. Ketiga hal tersebut dapat memberikan pengarahan atau pengalaman moral hidup yang baik, dan memberikan kedewasaan dalam bersikap.
Lebih lanjut diungkapkan Lickona (dalam Gunawan, 2012:23) adalah pendidikan untuk membentuk kepribadian seseorang melalui pendidikan budi pekerti, yang hasilnya terlihat dalam tindakan nyata seseorang, yaitu: tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, kerja keras dan sebagainya. Sedangkan menurut Scerenco (dalam Samani dan Haryanto, 2012:45) pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai upaya yang sungguh-sungguh dengan cara, di mana kepribadian positif dikembangkan, didorong dan diberdayakan melalui keteladanan, kajian (sejarah dan biografi pra bijak dan pemikir besar), serta praktik emulasi (usaha yang maksimal untuk mewujudkan hikmah dari apa-apa yang dipelajari).
Adapun pengertian karakter menurut para ahli adalah sebagai berikut:
- Scerenco mendefinisikan karakter sebagai atribut atau ciri-ciri yang membentuk dan membedakan ciri pribadi, ciri etis, dan kompleksitas mental dari seseorang, suatu kelompok atau bangsa (Samani dan Hariyanto, 2012:12).
- Herman Kertajaya mengemukakan bahwa karakter adalah ciri khas yang dimiliki seseorang dan ciri khas tersebut adalah asli mengakar pada kepribadian seseorang tersebut, dan merupakan mesin pendorong bagaimana sesorang bertindak, bersikap, berujar, dan merespon sesuatu (Asmani, 2012:28).
- Winnie memahami bahwa istilah karakter memiliki dua pengertian tentang karakter memiliki dua pengertian tentang karakter. Pertama, ia menunjukkan bagaimana seseorang berprilaku tidak jujur, kejam atau rakus, tentulah seseorang orang tersebut memanifestasikan prilaku buruk. Sebaliknya apabila sesorang berprilaku buruk. Sebaliknya, apabila seseorang berprilaku jujur, suka menolong, tentulah orang tersebut memanifestasikan karakter mulia. Kedua, istilah karakter erat kaitanya dengan personaliti. Seseorang baru bisa disebut orang yang berkarakter apabila tingkah lakunya sesuai dengan kaidah moral (Gunawan, 2012:2)
Dari beberapa pengertian yang dijelaskan di atas, dapat dinyatakan bahwa karakter adalah kualitas atau moral, akhlak, atau budi pekerti individu yang merupakan kepribadian khusus, yang menjadi pendorong dan penggerak, serta membedakanya dengan individu lain. Seseorang dapat dikatakan berkarakter, jika telah berhasil menyerap nilai dan keyakinan yang dikehendaki masyarakat, serta digunakan sebagai moral dalam hidupnya.
Berbeda dengan pendidikan informal, Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2003 pasal 27 ayat (1) tentang pendidikan informal adalah pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri (Suparlan, 2004:169).
Bilamana dihubungkan dengan pranata-paranata pendidikan informal di Muna, maka kegiatan pendidikan yang dimaksud adalah kegiatan pendidikan yang berlangsung dalam lingkungan keluarga yang bersifat mandiri, tidak terikat oleh aturan-aturan formal, jangka waktu atau durasi waktu tetapi dia berlangsung secara alamiah dan sesuai dengan momentum perkembangan manusia sejak dalam kandungan sampai kepada manusia dewasa.
Keluarga merupakan lembaga pertama dalam kehidupan seorang anak untuk belajar dan mengatakan sebagai makhluk sosial. Dalam keluarga umumnya anak melakukan interaksi yang intim. Keluarga adalah sekumpulan orang yang dihubungkan oleh ikatan perkawinan, adopsi, kelahiran yang bertujuan menciptakan dan mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional dan sosial dari tiap anggota keluarga (Duval, dalam Setiadi 2008). Slameto (2003) memberi pengertian keluarga sebagai lembaga pendidikan yang pertama dan utama bagi anak-anaknya baik pendidikan bangsa, dunia, dan negara sehingga cara orang tua mendidik anak-anaknya akan berpengaruh terhadap belajar. Sedangkan (Mubarak, dkk, 2009) keluarga merupakan perkumpulan dua atau lebih individu yang diikat oleh hubungan darah, perkawinan atau adopsi, dan tiap-tiap anggota keluarga selalu berinteraksi satu dengan yang lain.
Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukanya dalam suatu sistem (Mubarak, dkk. 2009). Peran merujuk kepada beberapa set perilaku yang kurang lebih bersifat homogen, yang didefinisikan dan diharapkan secara normatif dari seseorang peran dalam situasi sosial tertentu.
Menurut Setiadi (2008) peran keluarga adalah tingkah laku spesifik yang diharapkan oleh seseorang dalam konteks keluarga. Jadi peran keluarga menggambarkan seperangkat perilaku interpersonal, sifat, kegiatan yang berhubungan dengan individu dalam posisi dan situasi tertentu. Peranan individu dalam keluarga didasari oleh harapan dan pola perilaku dari keluarga, kelompok dan masyarakat.
Lebih jauh diungkapkan Setiadi bahwa setiap anggota keluarga mempunyai peran masing- masing. Peran ayah yang sebagai pemimpin keluarga yang mempunyai peran sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung atau pengayom, pemberi rasa aman bagi setiap anggota keluarga dan juga sebagai anggota masyarakat kelompok sosial tertentu. Peran ibu sebagai pengurus rumah tangga, pengasuh dan pendidik anak-anak, pelindung keluarga dan juga sebagai anggota masyarakat kelompok sosial tertentu. Sedangkan peran anak sebagai pelau psikososial sesuai dengan perkembangan fisik, mental, sosial dan spiritual.
Orangtua memiliki peran kunci dalam menentukan tingkat keberhasilan pendidikan karakter. Dengan pernyataan lain, orang tua memiliki peranan strategis dalam menentukan keberhasilan pengembangan karakter sukses anak. Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang dalam keluarga pengasuhan tidak hanya dilakukan oleh ayah ibunya. Akan tetapi terdapat anggota lain yang turut mengambil peranan dalam mengasuh dan mendidik anak.
Pendidikan karakter hendaknya diutamakan dan dimulai sejak anak itu berada di lingkungan yang terkecil yaitu keluarga. Sebab sejak di dalam kandungan bahkan setelah dilahirkan selalu berada di lingkungan keluarga khususnya dekat dengan orang tuanya. Pendidikan karakter dalam keluarga dapat dilakukan sedini mungkin secara perlahan, pertama, anak dibiasakan hidup dalam lingkungan positif. Orang tua dan orang-orang disekitar rumah harus mendemonstrasikan karakter positif dan keimanan seperti berdoa, berbagi, berkata sopan dan jujur. Selanjutnya direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari mengajarkan berdoa sebelum tidur. Kebiasaan positif seperti ini lambat laun akan menjadi bagian dari pembentukan karakter anak.
Fungsi pertama orang tua dalam kontek pengembangan karakter anak adalah sebagai model peranan. Orang tua memainkan peran penting dalam penanaman berbagai macam nilai kehidupan yang dapat diterima dan dipeluk oleh anak. Anak lebih banyak meniru dan meneladani orang tua, entah itu dari cara berbicara, cara berpakaian, cara bertindak, dan lain-lain. Orang tua tetap menjadi pedoman bagi pembentukan nilai-nilai pada pola tingkah laku yang diakui sisi oleh anak dalam masa awal perkembangan hidupnya.
Keluarga adalah tempat pertama dan utama di mana seorang anak dididik dan dibesarkan. Fungsi keluarga sebagai wahana untuk mendidik, mengasuh, dan mensosialisasikan anak, mengembangkan kemampuan seluruh anggotanya agar dapat menjalankan fungsinya di masyarakat dengan baik, serta memberikan kepuasan dan lingkungan yang sehat guna tercapainya keluarga sejahtera dan tempat pembentukan karakter anak yang utama, terlebih pada masa awal pertumbuhan mereka sebagai manusia. Selain memiliki fungsi pertama tempat sang anak menjalani apa yang di sebut sosialisasi, anak banyak belajar dari cara bertindak, cara berfiir orang tua. Merekalah yang menjadi model peran pertama dalam hal pendidikan nilai.
Seorang anak dalam proses tumbuh kembangya dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, dari lingkungan mikro sampai makro. Peran keluarga dalam pendidikan, sosialisasi, dan penanaman nilai kepada anak adalah sangatlah besar. Menurut Ratna Mawangi (dalam Kusuma, 2011:5), bahwa anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter apabila dapat tumbuh pada lingkungan yang brekarakter, sehingga fitrah setiap anak yang dilahirkan suci dapat berkembang secara optimal.
Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan wahana pertama dan utama bagi pendidikan karakter. Apabila keluarga gagal melakukan pendidikan karakter pada anaknya, maka akan sulit bagi institusi lain di luar keluarga untuk memperbaikinya. Kegagalan keluarga dalam membentuk karakter anak akan berakibat pada tumbuhnya masyarakat yang tidak berkarakter, oleh karena itu setiap keluarga harus memiliki kesadaran bahwa karakter bangsa sangat tergantung pada pendidikan karakter anak.
METODE
Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Kirk dan miller dalam (Lexy J.Moleong, 2009) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada penggamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan hubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Metode yang digunakan dalam penulisan adalah menggunakan telaah pustaka, dokumen, dan hasil wawancara dengan tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh agama serta tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap mengetahui masalah yang dilaksanakan dalam waktu yang tidak kaku sehingga sifatnya flesibel. Penulis tidak membuat jadwal dan acuan khusus untuk mencari data-data yang dimaksud, tetapi setiap saat dan kesempatan selalu berusaha untuk mengimpun data-data tersebut bahkan penulis menjadi pelaku dan pelaksana.
PEMBAHASAN
Penelitian ini di lakukan masyarakat Muna pada tahun 2016. Masyarakat Muna memiliki keragaman tradisi yang telah diciptakan oleh orang-orang terdahulu, yang bersentuhan langsung dengan pranata-pranata pendidikan dalam lingkungan keluarga dan masyarakatnya. Tradisi dan budaya lokal telah diwariskan secara turun temurun baik itu cerita rakyat (mitos, legenda), hukum adat, upacara-upacara adat maupun asal usul masyarakat dan terbentuknya pulau Muna.
Tradisi dan budaya lokal tersebut yang terkait langsung dengan lingkungan keluarga masih sering dipraktikkan oleh masyarakat Muna karena banyak mengandung nilai dan norma yang wajib dipedomani.Tradisi dan budaya lokal tersebut di antaranya terkait dengan lingkaran hidup (life cycle) manusia, seperti kasambu (penyuapan) yakni tradisi dilakukan bagi perempuan yang setelah kehamilannya berumur 7 bulan, kawoto tradisi menantikan kelahiran anak pertama, sariga yakni tradisi menanti kelahiran anak berikutnya bilamana berbeda jenis kelamin anak pertama, kampua yakni tradisi pengguntingan rambut atau aqiqah, kafofinda yakni tradisi menginjakkan kaki ke tanah saat bayinya berumur satu tahun, kangkilo (khitanan), katoba (bertobat), karia yakni tradisi pingitan bagi gadis menjelang dewasa, dan sebagainya. Di antara tradisi tersebut di atas artikel ini akan difokuskan pada tradisi upacara karia sebagai kekayaan khasanah budaya daerah yang masih tetap bertahan pada masyarakat Muna. Tradisi upacara karia umumnya dilakukan oleh masyarakat suku Muna ketika anak gadisnya telah menginjak dewasa (usia 15-16 tahun) dengan memperhatikan tanda-tanda khusus, yakni telah mengalami haid, buah dadanya sudah tampak dan kulitnya semakin halus. Upacara karia ini merupakan salah satu tanggung jawab kedua orang tuanya sebelum anak gadisnya dinikahkan (Couvreur, 2001:162). Upacara ini dilakukan dengan harapan bahwa setelah dilaksanakan upacara karia maka dianggap lengkaplah proses pembersihan diri secara hakiki.
Kunci ketertiban masyarakat terletak pada norma yang mereka bangun kemudian norma tersebut dianut, dipatuhi dan dipedomani. Norma berperan terhadap pengendalian pola sikap, piker dan perilaku individu ketika dia berinteraksi dengan yang lain dalam masyarakat. Sistem norma yang mereka miliki diwariskan dan dikembangkan dari generasi ke generasi berikutnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan.
Masyarakat Muna menyadari akan hal itu bahwa setiap manusia harus ditanamkan norma-norma sesuai dengan tahapan perkembangan fisik dan kejiwaan manusia. Tahapan tersebut tampak terlihat mistis, karena kurang dapat dijangkau oleh akal sehat. Hal ini dapat dipahami oleh karena tahapan tersebut dipengaruhi ajaran tasawuf yang mendominasi awal penyebaran Islam di daerah ini (La Fariki, 2010:1). Tahap-tahap perubahan fisik tersebut: a) perkembangan janin dalam kandungan, b) kelahiran, c) penanggalan tali pusat, d) permulaan tumbuh gigi, e) penanggalan gigi pertama, f) mimpi basah pertama bagi laki-laki dan permulaan haid bagi perempuan hingga pertumbuhan tinggi badan maksimal atau telah hidup dengan pasangannya.
Perubahan fisik tersebut diikuti pula oleh perubahan psikologi, sehingga setiap penanaman norma harus disesuaikan dengan perubahan fisik dan kejiwaan manusia. Penanaman norma disediakan oleh lembaga-lembaga pendidikan yang semuanya bertujuan untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia. Peserta yang menamatkan lembaga-lembaga pendidikan tersebut kadang diakhiri dengan upacara tradisional.
Pendidikan Anak Saat Usia Perkembangan Janin Masih di Dalam Rahim Ibu
Dalam tradisi masyarakat Muna, jika kehamilan pertama bagi seorang perempuan yang telah menikah, wajib dilakukan upacara Kasambu. Seperti dalam ungkapan yang berbunyi mahengga seghonu ghunteli (artinya: sekalipun hanya telur satu biji asalkan dilakukan Kasambu. Kasambu merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Muna. Menurut kepercayaan mereka bahwa setiap fase yang berkaitan dengan siklus kehidupan setiap individu merupakan sesuatu hal yang penting untuk dilakukan ritual untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Kasambu merupakan upacara peralihan dalam siklus kehidupan masyarakat Muna. Fase ini ditandai oleh perubahan tali pusat janin yang semakin mengecil, sementara metabolisme tubuh sudah semakin matang, sehingga ia terpaksa harus lahir, karena kebutuhan bayi tidak sanggup lagi disuplai oleh ari-arinya.
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Arnold Van Gennep (dalam Daeng, 2008:145), bahwa dalam setiap masyarakat, kehidupan sosial secara berulang dengan interval tertentu memerlukan regenerasi. Setiap perubahan dalam pertumbuhannya, dapat terjadi krisis-krisis mental yang berpengaruh terhadap jiwa seseorang. Untuk itu diperlukan upacara penunjang siklus hidup seseorang
Pasangan suami-istri yang akan melahirkan anak pertama diwajibkan mengikuti lembaga pendidikan yang disebut “Kasambu“ (bahasa Muna) yang berarti suapan. Penyelenggaraan lembaga pendidikan informal ini dimulai ketika janin telah berumur kurang lebih 8 bulan atau sebulan sebelum kelahiran. Maka pasangan suami istri dididik bagaimana mempersiapkan kelahiran dan merawat bayi. Lembaga pendidikan yang sifatnya informal merupakan suatu bentuk pemberitahuan kepada masyarakat supaya bersiap-siap menyambut anggota baru sekaligus sebagai isyarat kasat mata kepada janin bahwa dia bersiap memasuki alam baru yaitu alam dunia.
Lembaga pendidikan ini hanya diwajibkan pada kelahiran anak pertama dari hasil pernikahan, sedangkan untuk kelahiran anak berikutnya tidak lagi diwajibkan untuk di Kasambu. Sehari sebelum pelaksanaan Kasambu pihak keluarga khususnya ibu-ibu mempersiapkan bahan haroa (beberapa jenis makanan yang akan ditata dalam baki), seperti: ketupat, ayam, telur, kue cucur, kue waje, dan air gula. Pada waktu yang telah ditentukan, pasangan suami istri yang akan di Kasambu duduk di atas lesung yang telah dipersiapkan. Mengenakan sarung (bheta) sebatas dada (istilah bahasa Muna: kabonto) tanpa mengenakan baju. Sarung yang dikenakan di dalamnya dilapisi kain berwarnah putih. Kain berwarnah putih sebagai simbol kesucian dan bersih. Hal tersebut dimaksudkan agar bayi di dalam kandungan dapat lahir dengan selamat tanpa cacat. Selanjutnya dilakukan (haroa) yakni pembacaan doa selamat menurut agama Islam sekaligus pemberian wejangan atau ilmu untuk persiapan menyambut kelahiran dan pelajaran kepada pasangan suami istri tentang bagaimana merawat dan mengasuh bayi. Kemudian acara ini diakhiri dengan suapan, suapan dimulai suami istri saling menyuap menyuap. Apabila selesai maka suapan dilanjutkan oleh keluarga dekat dengan menyuap salah seorang di antara suami atau istri, di mulai oleh pejabat agama, kemudian dilanjutkan oleh hadirin yang datang menyaksikan upacara Kasambu. Bilamana ada yang berkenaan dari keluarga dapat menyumbangkan uang sesuai kerelaan kepada sang suami istri.
Berkaitan dengan hal tersebut dijelaskan bahwa perkembangan pertumbuhan manusia dapat diikuti dari permulaan benih laki-laki membuahi benih perempuan yang disebut proses fertilisasi atau pembuahan (fertilization) Conny R (2008:69). Di sini kita akan mengikuti bagaimana sel janin sesudah 14 hari membagi diri menjadi beribu-ribu sel dan kemudian terjadi beberapa lapisan sehingga setelah dua bulan janin tersebut akhirnya berbentuk anak.
Dengan demikian, maka lembaga pendidikan Kasambu atau suapan pada masyarakat Muna adalah bagaimana sejak dalam kandungan, sang janin sudah diberikan pendidikan melalui ibu/bapaknya. Bagaimana beribu-ribu sel yang merupakan cikal bakal dari janin menjadi sel-sel yang sehat yang selanjutnya menjadi janin yang tumbuh sehat. Suapan makanan pada saat Kasambu adalah makanan-makanan yang bergizi tinggi yang diharapkan sang janin tidak akan kekurangan gizi dan secara ilmiah hal ini akan menghindari penyakit yang sering menimpah janin yang sering kita lihat pada bayi-bayi yang dilahirkan pada masyarakat miskin di pedesaan yang disebut penyakit busung lapar.
Pendidikan Anak pada Saat Setelah Kelahiran
Anak yang baru lahir pasti langsung menangis. Dia menangis karena dia merasakan perubahan lingkungan yang drastis berupa perubahan suhu lingkungan dari 37 derajat celcius ketika berada dalam rahim ibunya menjadi 30 derajat celcius. Namun ahli tasawuf menafsirkan bayi yang menangis, karena ia menangisi rezekinya yang dia harus cari dengan susah payah pada umur yang ditetapkan oleh Allah swt. di dunia ini. Dia menggenggam umur di tangan kanan dan menggenggam rezekinya di tangan kiri (La Lariki, 2010:9).
Bayi yang baru lahir tidak diperkenankan dibawa keluar dari ruangan persalinan sebelum tali pusatnya tanggal atau terlepas. Hal ini disebabkan bayi yang baru lahir sangat rentan dengan perubahan lingkungan, sehingga dia butuh waktu untuk penyesuaian diri.
Bayi yang baru lahir diadzankan di telingga kanan dan diqamatkan di telinga kiri. Ari-arinya diletakkan dalam tempurung kelapa yang telah dibuka dagingnya kemudian dibungkus kembali sabutnya seperti semula. Ari-ari disebut kakak karena dialah yang melindungi sang bayi sewaktu masih dalam kandungan. Jasa ari-ari diperingati pada saat tertentu oleh sang bayi jika telah dewasa, karena keduanya dianggap tetap berhubungan, walau secara fisik ari-arinya telah hancur. Sering penyakit yang diderita seseorang berkaitan dengan ari-arinya.
Orang tua diberi batas waktu sampai bayi berumur 40 hari untuk memberikan sebuah nama kepada si bayi yang baru lahir. Orang yang paling berwenang memberikan nama yaitu ayah, ibu, kadang-kadang kakek atau nenek bayi yang bersangkutan atau anggota keluarga lain yang berpengaruh.
Umumnya bayi laki-laki diawali dengan sebutan “La“ sedangkan perempuan diawali dengan kata “Wa”. Penggunaan kata “La“ dan “Wa” pada perempuan diyakini sebagai simbol dari kalimat tauhid (La Fariki, 1997:20-21). Makna awalan ini sama dengan ketika bayi diadzankan dan diqamatkan yaitu bentuk peringatan kepada si anak supaya kelak tidak melupakan janjinya kepada Allah swt ketika rohnya dipersatukan dengan jasadnya dalam rahim ibunya. Oleh karena itu kata “La” di depan laki-laki merupakan emanasi kalimat tauhid yang pertama La Illaha Illallahu, sedangkan kata “Wa” merupakan emanasi dari kalimat tauhid kedua yaitu Wa ashadu Anna Muhammadar Rasulullah yang keduanya tidak dapat dipisahkan. Apabila dipisahkan maka keimanan seseorang tidaklah sempurna.
Untuk membedakan dengan awalan “La” pada nama-nama biasa, maka “La” dan “Wa” dipisahkan dari nama asli atau nama lamanya. Contoh La Temba, Wa Safihani dan Wa Naali. Jika bayi yang lahir berasal dari kalangan Kaomu, maka nama “La“ “Wa” diikuti dengan “ Ode” kemudian diikuti oleh kata lain yang dianggap cocok untuk nama si bayi yang bersangkutan. Kata Ode bermula dari raja Muna ke-13 Sangia La Tugho yang memerintah tahun 1671 – 1716 M. Dia memberikan kepada anaknya La Ode Husain hasil perkawinannya dengan Wa Sope. Kata Ode berasal dari panggilan La Ode Husain yang ketika lahir dinyanyikan dengan lagu “ Lakaode-ode” oleh perawatnya dari Labora. Kata Ode kemudian ikut digunakan kepada bangsawan yang hidup pada saat itu. Kata Ode ditafsirkan oleh para ulama pada saat itu sebagai manusia yang terbaik atau insan kamil atau manusia yang paling taqwa yang direpresentasikan oleh manusia-manusia yang menunjukan perbuatan-perbuatan yang terpuji, baik dan mulia serta melindungi orang lain (La Fariki, 1997:23).
Kata “La“ dan “Wa” dianggap juga merupakan bagian dari bentuk pembinaan orang tua kepada anak-anaknya agar mereka tidak melupakan janjinya dengan Allah swt, waktu rohnya akan disatukan dengan jasadnya mengakui kebesaran dari Allah swt. Dan ingatlah ketika Tuhannmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman“ Bukankah aku ini Tuhanmu? mereka menjawab betul Engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi, Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lemah terhadap ini (ke Esaan Tuhan) Q.S Al A’Raaf (7) : 172. Kata “La” dan “Wa“ diyakini akan memberiakan pengaruh yang besar kepada seseorang selama dia masih hidup di dunia, sehingga para orang tua menggunakan kedua kata ini untuk anak-anak mereka (La Fariki, 2009:22)
Nama laki-laki tidak diawali dengan “A” sebagaimana kata Asyhadu An La Illaha Illallahu, karena pernyataan dianggap sudah diucapkan pada saat dia berada dalam alam rahim, sehingga laki-laki memakai awalan “La” sedangkan kata Wa Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dipakai karena baru diucapkan setelah lahir di dunia ini, sehingga perempuan menggunakan awalan “Wa”.
Pemberian nama selalu hati-hati, karena diyakini bahwa nama di dunia juga berlaku diakhirat. Oleh karena itu nama harus dicarikan kata-kata yang baik. Orang Buton dan orang Muna menganggap nama memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan si anak baik fisik maupun psikologis. Pengaruh tersebut diyakini berdampak pada kesehatan, rezeki dan kelakuan sehari-hari. Orang yang sakit-sakitan sering dikaitkan pula dengan namanya yang tidak cocok, sehingga harus diubah. Demikian pula rezeki juga dipengaruhi oleh nama. Seseorang yang senantiasa mendapat sial sering dikaitkan dengan namanya demikian pula orang yang sering berkelakuan buruk sehingga perlu namanya diubah.
Oleh karena itu banyak nama bayi yang lahir dicarikan kata-kata dari kitab suci alquran untuk menangkal semua kemungkinan buruk yang akan dialami oleh sang bayi kelak setelah dewasa, nama adalah doa, karena itu nama-nama yang sesuai dengan alquran berarti permohonan manusia kepada Allah swt sesuai apa pengertian nama itu, bahkan dalam sebuah kata-kata bijak apa arti sebuah nama. Namun demikian sebahagian besar masyarakat yang kurang faham, masih menggunakan tradisi lama yaitu menggunakan peristiwa alam ketika si bayi dilahirkan, nama-nama yang natural misalnya nama tempat, nama buah dan lain-lain, bahkan dikaitkan dengan sikap-sikap orang tua atau kerabatnya. contoh : La Pili diambil ketika sikap orang tuanya sebelum anak dilahirkan suka pilih-pilih atau nama La Piliha ketika lahir berlangsung pemilihan umum.
Pendidikan Anak pada Saat Penanggalan Tali Pusat
Tali pusat yang tanggal atau terlepas merupakan pertanda bahwa si anak melepaskan diri secara resmi denga ari-arinya. Seiring dengan penanggalan tali pusat, maka si anak dapat merespon lingkungan sekitarnya, karena ia sudah dapat mendengar bunyi dan melihat warna sebagaimana makna dari alquran Surat An Nahl (16): 78 yang artinya: Dan Allah mengeluarkan kamu dalam perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur.
Bilamana tali pusat si bayi sudah tanggal maka kedua orang tuanya diwajibkan menyesuaikan atau mendidik bayinya dengan lingkungan sekitarnya. Anak yang baru lahir tidak diperkenankan langsung dibawa keruangan yang lain dan menyentuh, tanah, melainkan harus melalui rangkaian upacara. Hal ini bertujuan, selain sebagai persiapan adaptasi dengan lingkungan juga sebagai isyarat kepada si anak tersebut bahwa dia bersiap-siap memasuki lingkungan baru.
Waktu pelaksanaanya kira-kira bayi telah berumur tujuh hari setelah bayi dilahirkan oleh ibunya. pemindahan bayi dilaksanakan oleh pejabat agama. Bahasa Muna pemindahan ruangan disebut dengan “Folima”, sedangkan penyentuhan kaki bayi yang pertama dengan tanah disebut dengan “Kafofinda” atau “Kafosambu” (Bukan Istilah dalam Pingitan).
Apabila bayi telah melalui lembaga atau pranata “Kafofinda” atau “Kafosampu”, maka orang tuanya wajib menyelenggarakan sebuah pranata pendidikan yang disebut “Kampua” atau aqiqah. Biasa disebut pula pengguntingan rambut atau “Kaalano wulu” Syarat pranata ini yaitu bayi telah berumur 40 hari. Apabila orang yang mampu, maka biasanya diikuti dengan penyembelihan 1 ekor kambing bagi anak perempuan dan 2 ekor kambing bagi anak laki-laki, hal ini sesuai dengan sunnah dalam agama Islam. Pemotongan rambut dimulai dilakukan pada 3 tempat yaitu di kepala bayi 1) di samping kanan, 2) samping kiri dan 3) di ubun-ubun. Pemotongan rambut dimulai oleh pejabat agama kemudian diikuti oleh anggota keluarga. Rambut yang dipotong disimpan baik-baik oleh orang tua dan akan dikubur bersama bila pemilik rambut tersebut meninggal dunia.
Pendidikan anak pada saat permulaan tumbuh gigi
Perubahan yang menyertai anak apabila dia mulai tumbuh gigi, yaitu sang anak mulai mengenal ibu dan bapaknya dan membedakannya dengan orang lain, dengan demikian anak tersebut diwajibkan mengikuti pendidikan yang dalam bahasa Muna di sebut Sariga. Sariga diikuti oleh anak yang berumur 1 – 10 tahun.
Prosesi ini diawali dengan memukul gendang sesuai irama lokal dan anak dimandikan sambil menyandarkan kepala si anak pada lantai yang telah dipersiapkan sebanyak 7 kali mengikuti irama gendang. Acara ini berlangsung setiap pagi dan sore hari selama 4 hari dan acara ditutup dengan doa selamat. Makna prosesi ini supaya anak kelak tidak menjadi manusia durhaka, tetapi selalu menghormati orang tuanya. Anak dilatih sejak dini agar mereka patuh terhadap orang tuanya dan beradaptasi dengan lingkungannya.
Pendidikan Anak pada Saat Penanggalan Gigi Pertama
Gigi pertama yang tanggal menandahkan anak melepaskan status balita menjadi kanak-kanak. Rasa ingin tahu terhadap perbedaan dan perubahan lingkungan semakin tinggi, sehingga sang anak membutuhkan pendidikan yang terarah supaya tumbuh dengan pribadi yang baik.
Setiap gigi yang tanggal menurut orang Muna harus disimpan dilubang batu. Kepercayaan ini merupakan bagian kepercayaan bahwa manusia berasal dari tanah, sehingga ia meninggal dunia harus kembali ke tanah. Gigi berasal dari batu sehingga gigi yang tanggal harus dikembalikan ke tempat asalnya yaitu batu. Apabila seorang anak mulai menanggalkan giginya maka dia mulai dipersiapkan untuk mengikuti lembaga “Katoba”. Lembaga pendidikan ini diikuti oleh anak yang telah berumur 10 tahun atau (si anak usai disunat atau dikhitan) atau (si anak telah akil baligh atau si anak telah dapat membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk).
Orang tua dikenakan kewajiban supaya anaknya mendapatkan pendidikan ini. Bahasa Muna sering lembaga pendidikan ini dengan sebutan “Kangkilo”. Peraturan “Katoba” yaitu si anak diberi pakaian muslim atau adat yang paling bagus dan masing-masing memegang satu ujung kain putih sedang ujung lainnya dipegang oleh si pengajar yaitu pejabat agama. Dalam lembaga ini diajari berbagai materi pengetahuan. Materi pokok yang diajarkan yaitu dua kalimat syahadat “ Asyhadu Anlaa illaha Illallah Wa Asyahadu Anna Muhammadar Rasulullah” sambil dibacakan artinya “Aku bersaksi bahwa Tiada Tuhan yang disembah selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW merupakan utusan Allah”. Sedangkan pengajarnya adalah pejabat agama dan pejabat kampung, walau sifatnya lebih didominasi oleh monolog yaitu dari satu pihak saja, yakni dari sang pengajar. Pengajaran materi pokok inilah yang menyebabkan “Katoba” sering disebut sebagai acara pengislaman seorang anak, karena dia menyatakan kesaksiannya dihadapan orang banyak.
Materi kedua adalah bahasa “Toba”. Intinya adalah ajaran rukun iman dan rukun Islam dan analoginya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari analogi ini yaitu agar selain si anak tetap meyakini rukun iman dan rukun Islam, juga mereka supaya menghormati orang tua, kakak, adik, teman-teman dan alam sekitarnya seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan. Keenam rukun iman yang diajarkan yaitu: (1) percaya kepada Allah swt, (2) percaya kepada Malaikat, (3) percaya kepada kitab-kitabnya, (4) percaya kepada nabi dan rasulnya, (5) percaya kepada hari kiamat/kematian, (6) percaya kepada qodho dan qadar. Manifestasi kepercayaan tersebut kemudian dianologikan pada doktrin berikut: Sayangi Ayahmu, karena Ayahmu sebagai emanasi Allah swt, Sayangi Ibumu Karena Ibumu emanasi dari Nabi Muhammad saw, Sayangi Kakakmu karena kakakmu emanasi Malaikat, Sayangi Adikmu karena adikmu emanasi kitab quran, Sayangi Sesamu karena mereka emanasi hari akhirat, Sayangi hewan dan tumbuh-tumbuhan karena mereka emanasi qadha dan qadar. Setelah itu kemudian si anak diwajibkan melaksanakan rukun Islam yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat ,salat, puasa, zakat dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu.
Materi lain adalah tata susila atau sopan santun, ajaran-ajaran tersebut yaitu bekerja keras, jangan mengganggu orang lain, jangan mengambil hak orang lain tanpa minta izin, jangan berbohong, jangan menjadi saksi palsu apabila dibutuhkan, kalau lewat di depan orang lebih tua harus membungkuk dan merentangkan tangan kanan sambil mengucapkan kata “Tabea”. Si anak mulai diingatkan bahwa ia sudah masuk balig setelah selesai “Katoba”, sehingga semua perbuatannya akan mendapat balasan oleh Allah swt. Kebaikan akan dibalas dengan pahala dan keburukan akan dibalas dengan dosa.
Semua ucapan sang pengajar wajib dibalas dengan kata “Ya“ oleh sang murid atau “Umbe” (bahasa Muna). Acara Katoba ditutup dengan kata tobat bagi anak-anak yang dikatoba kemudian ditutup dengan pembacaan doa selamat dan hiburan. Khusus perempuan apabila setelah dikhitan diakhiri dengan “Posusu” bagi mereka yang telinganya belum dilobang untuk tempat anting-anting. Posusu berarti kegiatan melobang telinga dengan cara ditusuk dengan jarum sehingga tembus, kemudian jarum diganti dengan benang supaya lobang telinga tidak tertutupi oleh daging.
Pendidikan Anak Saat Mulai Mimpi Basah bagi Laki-Laki dan Haid bagi Perempuan
Mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan merupakan perubahan fisik yang diikuti pula oleh perubahan psikologi yang penuh dengan goncangan kejiwaan. Ilmu psikologi menyebut perubahan ini dengan sebutan puberitas yaitu peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan pertanda bahwa hormon-hormon tubuh mulai berproduksi, namun belum maksimal, karena energi tubuh masih dipergunakan untuk pertumbuhan tinggi badan.
Manusia yang telah mengalami masa ini diwajibkan mengikuti lembaga atau pranata “Kalego” bagi laki-laki dan “Karya” bagi perempuan. Prosesi “Kalego dilaksanakan ketika si anak laki-laki telah mengikuti pendidikan “Katoba”. Waktu pelaksanaanya hanya berlangsung 1 malam. Sang murid diberi pakaian bagus-bagus kemudiaan diajari lagi oleh pendidikan yang materi atau kurikulumnya mirip dengan “Katoba”. Sang murid di-lego yang berarti diarak sambil menampilkan dirinya di depan umum bahwa dia telah dewasa untuk menerima hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat.
Syarat utama “Kalego” yaitu apabila anak yang bersangkutan kira-kira berumur minimal 10 tahun. Dia diberi pelajaran supaya menghindari pergaulan bebas dengan wanita. Syarat utama pranata Karya yaitu apabila sang gadis telah berumur 15 tahun atau lebih. Pelaksanaannya bisa tepat pada umur tersebut atau jika ia akan dipinang oleh lelaki. Prosesi ini juga dilakukan setelah si anak menjalani prosesi “Katoba”. Gadis yang belum dipingit disebut “Kambua-bua”, sedangkan gadis yang telah dipingit disebut “Kalambe”. Pingitan dalam bahasa Muna berarti Karya bermakna festival atau pengumuman kepada khalayak ramai bahwa ada segolongan perempuan yang memasuki usia remaja, sehingga mereka dipuasakan supaya menjadi remaja yang baik. Prosesi ini merupakan tindak lanjut cerita di Muna bahwa Rasulullah Muhammad saw mengurung anaknya Sitti Fatimah ketika Fatimah mau dilamar oleh sahabat-sahabatnya. Rasulullah tidak ingin mengecewakan sahabat-sahabatnya dan beliau kemudian mengurung Sitti Fatimah. Setelah selesai dikurung ,maka wajahnya beragam dan orang yang berutung mendapatkan Sitti Fatimah yang aslinya ternyata Ali bin Abu Thalib.
Masa atau lama pingitan bervariasi. Golongan Kaomu selama 8 hari 8 malam sedangkan golongan walaka selama 4 hari 4 malam. Masyarakat Muna zaman dahulu pernah melaksanakan Karya selama 44 hari, mereka tidak diperkenankan keluar, apabila sang gadis melanggar, maka ia akan selalu sial baik bagi dirinya sendiri maupun untuk keturunannya. Oleh karena itu para orang tua si gadis yang dikaryakan turut mengawasi anaknya yang dikaryakan. Mereka selama dalam kurungan diwajibkan berpuasa dan hanya diberi makan 1 biji telur, 1 buah ketupat atau segenggam nasi putih pada pagi dan sore hari saja.
Mereka diberi pendidikan oleh pemandunya bagaimana menjadi perempuan yang baik, bagaimana menjadi istri yang baik dan bagaimana bergaul yang baik dalam masyarakat. Mereka juga diuji untuk menahan hawa nafsu dan bersikap yang baik. Setelah masa kurungan atau masa puasa usai, maka mereka dikeluarkan oleh pemandunya disambut oleh orang tua dan keluarga dengan bahagia. Mereka kemudian di bawa di suatu tempat untuk dirias untuk oleh mereka yang telah dipersiapkan oleh keluarganya. Usai dirias maka mereka dibawa ke ruang terbuka untuk disaksikan oleh umum atau calon suami. Mereka didudukkan di atas bangku atau panggung yang dibungkus dengan kain putih dan jalan di atas kain putih pula. Mereka menerima ucapan selamat dari hadirin, sebahagian di antara hadirin memberikan uang atau bingkisan sesuai kerelaan masing-masing. Salama kurungan para gadis dihibur dengan irama musik lokal yang digelar di luar kamar kurungan tiap pagi dan sore, bahkan jika kurungan telah memasuki hari ke dua menjelang penutupan, maka irama musik harus dilaksanakan semalam suntuk untuk membahagiakan para gadis bahwa puasa mereka segera akan berakhir. Acara ini ditutup dengan pembacaan doa yang dilaksanakan di dalam rumah bukan lagi di tempat terbuka. Dan esok harinya atau beberapa hari kemudian seluruh peserta dan diikuti oleh beberapa keluarga bersama petugas agama melaksanakan pelepasan mayang pinang di laut atau di sungai sebagai tanda lepasnya segala dosa-dosa yang diperbuat selama ini dan sebagai pertanda bahwa seseorang sudah memasuki usia gadis atau kalambe.
Pendidikan Anak Saat Pertumbuhan Tinggi Badan Maksimal atau Telah Hidup dengan Pasangannya.
Perubahan fisik ditandai oleh tinggi badan yang tidak mengalami perubahan lagi, namun hormon-hormon tubuh sudah berproduksi maksimal. Seiring dengan penambahan waktu, maka berbagai fungsi jaringan telah mulai mengalami penurunan seperti mata kabur, jantung, kolestrol, gula darah dan asam urat serta kanker.
Perubahan psikologi ditandai oleh perasaan tanggung jawab yang besar. Mereka yang belum menemukan pasangannya akan memikul tanggung jawab sebagai orang dewasa, sedang mereka yang sudah menemukan pasangannya akan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam rumah tangga. Suami akan mencari nafkah untuk istrinya sebaliknya istri membantu suami dan merawat anak-anak. Materi pendidikan pada manusia yang mengalami perubahan fisik ini tidaklah bersifat bimbingan, tetapi bersifat arahan oleh kominitas masyarakat. Hal ini disebabkan oleh karena Toba tidak menyediakan pranata untuk perubahan fisik ini. Mereka hanya mendapat pendidikan jika mereka melanggar norma oleh dewan kerajaan atau suatu kampung. Jabatan hakim dalam kerajaan Muna disebut Mintarano Bitara. Hakim memutuskan perkara berdasarkan hukum adat kemudiaan berubah menjadi hukum-hukum agama Islam.
PENUTUP
Dari pembahasan tersebut di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: wujud pendidikan manusia pada saat perubahan perkembangan Janin dalam rahim Ibu adalah suami-istri yang akan melahirkan anak pertama diwajibkan mengikuti lembaga pendidikan yang disebut “Kasambu” yang membutuhkan makanan-makanan yang bergizi tinggi agar jabang bayi sehat dan terhindar dari penyakit busung lapar.
Setelah fase kelahiran adalah penyesuaian dengan lingkungan yang baru, perubahan lingkungan yang drastis berupa perubahan suhu lingkungan dari 37 derajat celcius ketika berada dalam rahim ibunya menjadi 30 derajat celcius, sehingga perlu diberi nama dan perlindungan dari anasir-anasir dan aura negatif.
Pada saat penanggalan tali pusat adalah pemindahan ruangan disebut dengan “Folima”, sedangkan penyentuhan kaki bayi yang pertama dengan tanah disebut dengan “Kafofinda” atau “Kafosambu”. Wujud pendidikan manusia pada saat permulaan tumbuh gigi pada anak adalah yaitu sang anak mulai mengenal ibu dan bapaknya dan membedakannya dengan orang lain, dengan demikian anak tersebut diwajibkan mengikuti pendidikan yang dalam bahasa Muna di sebut Sariga, supaya anak tidak durhaka kepada ibu bapaknya. Kemudian dilanjutkan proses Katoba (Pengisalaman) intinya adalah pengucapan dua kalimat syahadat dan implemantasinya “syhadu Anlaa illaha Illallah Wa Asyahadu Anna Muhammadar Rasulullah” sambil dibacakan artinya “Aku bersaksi bahwa Tiada Tuhan yang disembah selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad saw. merupakan utusan Allah”.
Wujud Pendidikan manusia pada saat mulai mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan adalah dalam bentuk “Kalego” bagi laki-laki dan “Karya” bagi perempuan. Prosesi “Kalego dilaksanakan ketika si anak laki-laki telah mengikuti pendidikan “Katoba”. Waktu pelaksanaanya hanya berlangsung 1 malam. Sang anak diberi pakaian bagus-bagus kemudiaan diajari lagi oleh pendidikan yang materi atau kurikulumnya mirip dengan “Katoba”. Terakhir pada saat pertumbuhan tinggi badan maksimal atau telah hidup dengan pasangannya adalah tidaklah bersifat bimbingan, tetapi bersifat arahan oleh kominitas masyarakat. Hal ini disebabkan oleh karena Toba tidak menyediakan pranata untuk perubahan fisik ini.
Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka tidak cukup hanya ditempuh melalui pendidikan formal, nonformal melainkan dapat juga ditempu melalui pendidikan informal. Oleh karena itu pendidikan informal perlu terus digalakkan, karena disanalah internalisasi yang utama dan pertama bagi pembentukan karakter bagi seorang anak.
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Majid, dkk. 1998. Pendidikan Karakter Perspektif Islam. Bandung: Rosdakarya.
Asmani, Jamal Ma’mur. 2012. Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter
Di Sekolah. Yogyakarta: Diva press.
Binti Maunah 2009. Ilmu Pendidikan. Yogyakarta: Teras.
Chintya, Apsari Putri. 2015. Pengertian Pendidikan Formal. https://chintyaapsariputriixa13blog.wordpress.com/2015/02/23/pengertian-pendidikan-formal. Diunduh pada 02 Maret 2016.
Conny R. Semiawan. 2008. Penerapan Pembelajaran Pada Anak. Jakarta: PT. Indeks.
Couvreur, J. 2001. Sejarah dan Kebudayaan Muna. Kupang: Artha Wacana Press.
Eddy. 2009. “Kontinuitas Sejarah dan Pengembangan Kebudayaan Nasional dalam Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa”. Jurnal IPS. “vol” 17, (32), 1-6.
Daeng, Hans. 2008. Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan: Tinjauan Antropologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Gunawan, Heri. 2012. Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi. Bandung: Alfabeta.
Horton, Paul B & Hunt, Chester L. 1993. Sosiologi (8th editing) (Terjemahan dalam Bahasa Indonesia oleh Aminuddin Ram dan Tita Sobari. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Kusuma, Dharma. 2011. Pendidikan Karakter Kajian Teori dan Praktik di Sekolah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
La Fariki. 2010. Sistem Pendidikan “Toba” Pada Masyarakat Buton dan Muna Sulawesi Tenggara. Kendari: Komunika.
La Oba. 2005. Muna Dalam Lintasan Sejarah (Prasejarah – Reformasi). Bandung: Sinyo M.P
Lickona, Thomas. 1992. Educating For Character How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility. New York Toronto-London-Sydney-Auckland: Bantam Books.
Lickona, Thomas. 1991. Education of Caracter. (Terjemahan). Bandung: Alfabeta.(https://www.scribd.com/07ringkasan+buku+karackter+lickona/htm. Unduh pada tanggal 15 Februari 2017.
Majid, Abdul dan Andayani, Dian. 2011. Pendidikan Karakter Perspektif Islam. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Mubarak, Z, dkk. 2009. Manusia, Akhlak, Budi Pekerti dan Masyarakat. Depok: Lembaga Penerbit FE UI.
Moleong, J. Lexy. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda Karya.
Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025.
Samani, Muchlas & Hariyanto. 2012. Pendidikan Karakter Konsep dan Model. Bandung: Alfabeta.
Slameto. 2003. Belajar dan Faktor-Faktor Mempengaruhinya. Jakarta: Rineka Cipta.
Suparlan. 2004. Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, Dari Konsepsi Sampai Implementasi
Hikayat.