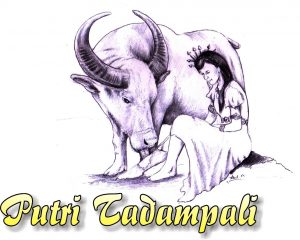Desa Anggopiu adalah salah satu desa dalam wilayah Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan sentra perajin tenun. Secara historis, tenun tradisional yang berkembang di Sulawesi Tenggara diperkirakan berawal di Buton. Tenun tradisional di daerah ini diperkirakan sudah ada sejak abad XVI, pada masa pemerintahan Sultan Dayanu Ikhsanuddin, sultan Buton yang memerintah pada tahun 1578 – 1615. Pada awalnya, keterampilan menenun hanya berkembang di lingkungan keraton. Kegiatan menenun dilakukan oleh dayang-dayang dan orang-orang di dalam kraton untuk memenuhi kebutuhan akan pakaian bagi golongan bangsawan dan kerabat kesultanan. Sejalan dengan permintaan dan kebutuhan akan pakaian semakin banyak, menyebabkan kegiatan menenun dikembangkan pula di luar kraton, khususnya dikalangan ibu-ibu dan remaja putri dalam wilayah kesultanan Buton.
Desa Anggopiu adalah salah satu desa dalam wilayah Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan sentra perajin tenun. Secara historis, tenun tradisional yang berkembang di Sulawesi Tenggara diperkirakan berawal di Buton. Tenun tradisional di daerah ini diperkirakan sudah ada sejak abad XVI, pada masa pemerintahan Sultan Dayanu Ikhsanuddin, sultan Buton yang memerintah pada tahun 1578 – 1615. Pada awalnya, keterampilan menenun hanya berkembang di lingkungan keraton. Kegiatan menenun dilakukan oleh dayang-dayang dan orang-orang di dalam kraton untuk memenuhi kebutuhan akan pakaian bagi golongan bangsawan dan kerabat kesultanan. Sejalan dengan permintaan dan kebutuhan akan pakaian semakin banyak, menyebabkan kegiatan menenun dikembangkan pula di luar kraton, khususnya dikalangan ibu-ibu dan remaja putri dalam wilayah kesultanan Buton.
Keterampilan menenun orang Buton kemudian disebarluaskan ke daerah-daerah sekitar, seperti Muna, Konawe dan Kendari. Khusus Konawe dan Kendari, tenun tradisional di daerah ini juga mendapat pengaruh dari Bugis, sehingga motif tenun mempunyai kemiripan dengan motif tenun Bugis. Walaupun mendapat dua pengaruh etnik yang berbeda, tenun tradisional di Konawe dan Kendari tidak mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini disebabkan karena orang-orang Konawe dan Kendari tidak terlalu meminati pekerjaan tenun, sehingga hanya beberapa desa (kampung) dan beberapa orang saja setiap kampung yang menggeluti pekerjaan tersebut. Rendahnya minat tersebut sangat terkait dengan karakteristik masyarakat yang lebih cenderung pada kegiatan ekonomi yang lain, seperti yang berkaitan dengan ekonomi nelayan dan pertanian, serta kerajinan anyaman.
Benang polyster, benang les, dan benang emas/perak merupakan bahan baku penenun. Benang polyster dan benang emas/perak biasanya digunakan sebagai benang pakan dan lungsi, benang ini bentuknya sangat halus dan elastis. Sedangkan benang les bentuknya lebih besar dan warnanya hanya putih, digunakan sebagai benang tambahan pada saat membentuk motif di kepala kain. Ketiga jenis benang ini biasanya digulung pada pedati yang berukuran kecil dan besar. Benang yang digulung dalam pedati kecil biasanya terdiri atas enam buah dalam satu dos. Sedangkan benang dalam gulungan besar biasanya terdiri atas dua buah dalam satu dos. Khusus benang les, karena penggunaannya relatif sedikit, maka gulungannya juga relatif kecil dan dapat dibeli per gulung. Untuk mendapatkan benang seperti tersebut di atas, perajin dapat membelinya langsung di toko-toko, baik di Unaaha maupun di Kendari.
Ada dua jenis peralatan yang digunakan oleh penenun di daerah ini, yaitu gedogan dan ATBM. Pada masa lalu hingga tahun 1980-an, penenun masih menggunakan satu alat tenun, yaitu gedogan. ATBM baru digunakan pada awal tahun 1990-an yang diperkenalkan oleh seorang pengusaha dari Kab. Wajo, Sulawesi Selatan. Kendati demikian, alat tenun gedogan masih tetap digunakan oleh sebagian penenun di Desa Puuwonua dan di Desa Tobimeita.
Kedua alat tenun tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan dalam hal produksi. Penenun yang menggunakan alat gedogan dapat menyelesaikan sehelai sarung selama tiga hingga tujuh hari. Sedangkan bila menggunakan ATBM dapat menyelesaikan sehelai sarung selama satu hari. Bahkan, bagi mereka yang sangat terampil dapat menyelesaikan tiga sarung selama dua hari.
Kain atau sarung yang diproduksi dengan alat gedogan lebarnya sekitar 65 x 400 cm, sehingga kain tersebut harus dipotong dua terlebih dahulu kemudian dijahit, lalu disambung kembali untuk mendapatkan sehelai sarung. Sedangkan kain yang diproduksi dengan ATBM lebarnya sekitar 130 x 200 cm, kain tersebut tidak perlu dipotong atau langsung saja disambung dengan cara dijahit. Kualitas kain yang diproduksi dari kedua jenis alat tersebut semuanya sama, yang membedakannya tergantung dari bahan benang yang digunakan.
Berdasarkan jenis kain yang diproduksi kebanyakan dalam bentuk sarung. Oleh karena sarung merupakan kelengkapan dari pakaian adat yang digunakan oleh kaum laki-laki dan perempuan. Untuk motif kainnya, etnik Tolaki memiliki motif yang disebut: (1) Motif balo gambere, yaitu motif kotak-kotak kecil dengan warna dasar hitam dan putih; (2) motif barik subbek, yaitu motif kotak-kotak dengan warna dasar hitam dan merah tua; (3) motif balo panta, yaitu motif kotak-kotak yang garis-garisnya terputus-putus dengan warna dasar yang agak gelap-gelap, seperti hitam, merah tua dan hijau tua. Semua motif tersebut memiliki kepala kain yang motifnya sama. Motif pada kepala kain tersebut terdapat garis-garis sebanyak tiga buah dengan warna yang berbeda-beda, seperti merah, kuning dan hijau. Selain itu, terdapat pula garis-garis berbentuk gunung (piramida) yang disebut pepokoasoa; serta terdapat pula garis-garis yang berbentuk ikat pinggang yang disebut tali-tali. Semua bentuk garis-garis tersebut dan pewarnaannya mengandung makna simbolik.
Proses distribusi kain tenun tradisional Tolaki dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung ke konsumen. Distribusi secara langsung biasanya terjadi bilamana konsumen mendatangi langsung usaha tenun untuk membeli atau memesan kain/sarung yang diinginkan. Melalui distribusi secara langsung ini, konsumen biasanya mendapatkan harga relatif murah dibanding jika membeli melalui toko atau pasar. Konsumen yang menempuh cara seperti ini biasanya yang berlokasi di dekat usaha tenun itu sendiri. Sedangkan distribusi tidak langsung dilakukan dengan cara menyalurkan hasil produksi melalui saluran-saluran perantara, seperti butik, toko, pasar tradisional dan pedagang keliling. Saluran-saluran distribusi tersebut tidak hanya berlokasi di Kabupaten Konawe, tetapi juga di Kendari dan daerah-daerah lainnya di Sulawesi Tenggara, bahkan di daerah-daerah atau di kota lain di luar Sulawesi Tenggara, seperti Makassar, Jakarta, Surabaya dan sebagainya.