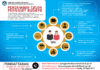Sekarang Gesek hanya nama sebuah kampung di Kelurahan Toapaya Asri, Kecamatan Toapaya. Dulu Gesek pernah menjadi tempat hunian yang cukup ramai dan berkembang. Dulu banyak etnis tionghoa yang bertempat tinggal di daerah tersebut. Dan kini yang menandai bahwa gesek bekas komplek pecinan adalah masih adanya kedai-kedai kopi yang dikelola orang tionghoa dan keberadaan kelenteng/topekong di bawah persimpangan gesek.
Nama gesek berasal dari istilah yang sederhana; dua benda atau lebih yang bersentuhan secara berlawanan. Secara mudahnya begitu.
Istilah gesek diambil dari sebuah aktivitas peng-gesek-kan kayu. Memotong kayu atau mengolah kayu pohon (logging) sehingga membentuk potongan-potongan bentuk papan atau yang lainnya. Dulu ada sebuah perusahaan pemotongan/pengolahan kayu yang dikerjakan secara manual. Perusahaan tersebut terletak di pinggir sungai di Batu 19 (KM 19). Menurut cerita sungai tersebut dulunya digunakan warga untuk mengangkut kayu dengan cara menghanyutkannya di aliran sungainya atau diangkut dengan perahu-perahu besar yang dapat melintasi sungai tersebut.
Dalam memotong atau membelah kayu gelondongan (logging) alat yang digunakan adalah gergaji tradisional yang membutuhkan dua orang untuk mengerjakannya. Cara pemakaiannya satu orang di atas dan satu orang lagi dibawah. Atau satu orang diujung gergaji kanan dan seorang lagi di ujung sebelah kiri: mereka saling mendorong dan menarik secara kompak. Aktivitas tersebut oleh warga sekitar disebut dengan menggesek.
Namun pandangan orang yang menyebut nama Gesek berasal dari aktivitas pemotongan kayu disangkal oleh beberapa orang yang lainnya. Menurut orang yang tidak sepakat dengan pendapat di atas mengamini jika gesek berarti memotong, namun obyeknya bukan kayu, melainkan bagian tubuh manusia.
Kapan tepatnya peristiwa tersebut terjadi? Mungkin sekitar abad 18 atau 19 M atau beberapa abad sebelumnya. Saat itu banyak etnis Tionghoa yang menguasai lahan-lahan perkebunan yang ditanami gambir dan sebagian tanaman karet. Banyak orang tionghoa didatangkan langsung dari negeri asalnya untuk mengurusi perkebunan gambir dan karet serta mengolahnya (mangsang). Hal ini karena melimpah dan banyaknya tanaman gambir dan karet yang harus dipelihara/diurusi. Saat itu dapat dikata yang banyak bekerja adalah orang-orang tionghoa; baik itu yang menjadi mandor maupun yang menjadi buruhnya. Banyak juga buruh-buruh berasal dari Jawa, Sumatera, dan daerah-daerah lainnya.
Sisi lain kehidupan para mandor atau orang tionghoa kaya adalah bahwa mereka mempunyai samsing (bodyguard, tukung pukul, centeng, pendekar) yang bertugas untuk mengawal dan menjaga rumah dan harta benda tuannya. Dan tidak terkecuali para samsing tersebut juga mengerjakan semua perintah majikannya, misalnya melenyapkan para buruh yang dianggap kurang ajar atauapun melakukan perlawanan terhadap majikannya.
Menurut cerita lisan kebanyakan yang dilenyapkan adalah para pekerjanya. Karena alasan tertentu seorang pekerja dapat dengan mudah dibunuh oleh para samsing. Cara melenyapkan nyawanya dengan cara lehernya digesek (dipotong). Dengan kata lain para samsing bertugas sebagai algojo. Kemudian tubuh orang-orang yang telah mati tersebut dibuang ke sungai (sungai itu kini juga disebut sungai Gesek) sehingga airnya berwarna merah.
Dahulu di kalangan mereka ada dua pilihan cara menghukum orang yang dianggap membangkang atau karena alasan tidak disenangi majikan, yaitu basah atau kering. Cara hukuman yang kering kering dengan potong leher, sedang cara basah dengan cara diceburkan ke dalam sumur yang cukup besar dan dalam. Sekarang sumur tersebut telah tiada akibat tertutupi oleh rimbun semak dan pohon-pohon.
Dahulu penduduk kampung ini banyak dari kalangan etnis Tionghoa yang telah beranak-pinak di Tanah Melayu ini. Hal ini dapat jadi disebabkan pada jaman dahulu orang-orang Tionghoa sengaja didatangkan dari Negeri Tirai Bambu, asalnya, secara langsung guna mengurusi perkebunan dan mengolah gambir. Pada saat itu gambir merupakan komoditas yang cukup besar. Terutama sebelum memasuki abad 20, Bintan dikenal sebagai penghasil gambir dengan kualitas bagus. Gambir olahan ini diekspor ke Singapura hingga India sebagai bahan pewarna kain. Selain gambir komoditas lainnya adalah karet.
Pada paruh awal abad 20-an banyak orang-orang Tionghoa mulai pindah ke kota-kota yang lebih ramai; Tanjungpinang atau Singapura. Sebagian yang lain tetap tinggal di hutan-hutan; setia mengurusi gambir dan karet. Migrasi besar orang tionghoa ke kota terjadi pasca peristiwa Konfrontasi dengan Malaysia dan Singapura. Pada saat itu gambir dan karet yang jumlahnya banyak tidak bisa dijual ke Malaysia dan Singapura sehingga membuat mereka frustrasi ekonomi. Beberapa pihak bisa menjual dengan cara menyelundup dengan menggunakan perahu-perahu.
Pasca Konfrontasi tanaman gambir dan karet banyak yang tidak produktif akibat tua dan mengering, hal ini akibat tidak adanya regenerasi tanaman gambir dan karet. Untuk mengatasi kondisi tersebut pemerintah pusat sempat menggalakkan tanaman cengkeh, namun tidak berhasil. Menurut ahli pertanian, sebagaimana menurut informan, tanah dan hawa daerah Bintan terlalu panas untuk tanaman cengkeh. Pohon cengkeh bisa tumbuh hanya beberapa waktu saja setelah agak besar tidak bisa berbunga akibat dahan dan daun-daunnya mengering.
Masa Penjajahan Jepang
Di daerah Bintan Timur pertambangan bauksit sudah dibuka saat penjajahan Belanda. Menurut cerita mantan pegawai PN. Aneka Tambang, Belanda baru melakukan survei kandungan tambang pada tahun 1920. Mulanya mereka survei tambang timah, sebagaimana yang terdapat di daerah Bangka-Belitong. Namun setelah diselidiki dan diteliti ternyata Pulau Bintan tidak mengandung timah, tapi bauksit. Belanda mulai melakukan pertambangan sekitar tahun 1936-an dengan mengambil para pekerja dari Bangka Belitung dan daerah-daerah lainnya. Kemudian pertambangan bauksit direbut Jepang ketika “Pasukan Asia Timur Raya” itu datang ke Pulau Bintan. Hal ini menyebabkan Belanda menyingkir keluar dari Pulau Bintan.
Agar tambang bauksit dapat terus berproduksi Jepang mendatangkan orang-orang Romusha dari Jawa dan orang-orang tionghoa dan keling (India) dari Singapura untuk dipekerjakan di pertambangan bauksit. Orang-orang jawa tersebut sebagian dipekerjapaksakan (Romusha) di pertambangan dan sebagian yang lainnya disuruh mengurusi tanaman di daerah di Toapaya. Peristiwa mendatangkan orang-orang Jawa tersebut terjadi antara 1942-1944.
Di Toapaya ini romusha dari Jawa tersebut disuruh untuk menanam ubi-ubian, sayur, dan tanaman pangan lainnya. Toapaya dijadikan basis tanaman pangan untuk menyuplai dan mencukupi kebutuhan pangan para pekerja tambang dan romusha lainnya. Tidak mengherankan jika Toapaya dijadikan sebagai daerah basis tanaman pangan hal ini karena tanahnya cukup subur dibanding daerah-daerah lainnya.
Kedatangan Jepang ke Pulau Bintan selain mimpi buruk bagi penjajah Belanda juga kalangan orang-orang tingohoa, khususnya bagi para toke (bos, majikan, mandor) dan keluarganya. Sebelum Jepang datang orang-orang tionghoa menempati posisi sosial yang diuntungkan secara ekonomi dan politik oleh Belanda. Mereka adalah para penguasa lahan di Tanah Melayu ini. Kenyamanan yang selama ini berjalan secara mapan dan tenang akhirnya porak-poranda. Tentara-tentara Jepang merampas harta benda toke (mandor, bos etnis tionghoa) dan memperkosa perempuan-perempuan tionghoa. Jika orang-orang tionghoa melawan tentara-tentara tersebut tidak segan membunuhnya. Untuk menyelamatkan diri dari kekejaman tentara “negeri samurai” tersebut banyak orang tionghoa yang memilih kabur ke dalam hutan-hutan; bersama keluarga dan sebagian harta benda yang bisa dibawanya. Seberapa lama orang-orang tionghoa tersebut mampu bertahan di tengah ketakutan dan setok makanan yang minim? Tentu terbatas waktu.
Salah satu keluarga tionghoa yang melarikan diri tersebut bernama Go Lai Hong. Mereka melarikan diri ke tepi-tepi sungai yang ada di Gesek. Keluarga marga Go ini merupakan keluarga kaya dan terpandang sebelum Jepang datang. Di tepi sungai tersebut, ada pula yang menyebutnya Sungai Go Lai Hong, mereka membuat pemukiman yang menghimpun keluarga besar marga Go. Dalam pelarian tersebut mereka berharap Jepang tidak akan lama menjajah mereka. Nyatanya Jepang berada di Pulau Bintan bertahun-tahun, sebagaimana terjadi juga di daerah lainnya di nusantara ini.
Di tengah pelariannya di hutan-hutan dan tepi-tepi sungai dengan jumlah makanan yang minim dan kecemasan yang memuncak mengakibatkan tidak sedikit dari orang-orang tionghoa tersebut akhirnya meninggal dunia karena kelaparan. Dan untuk menyelamatkan harta benda yang sempat dibawa dalam pelarian orang-orang tionghoa menyembunyikan harta-harta mereka dengan cara ditimbun dalam tanah/dikubur. Menurut cerita beberapa orang, waktu belakangan ini banyak warga masyarakat secara tidak sengaja menemukan “harta karun” berupa guci, beragam keramik, dan perhiasan emas.
***
Jauhar Mubarok
Penyuluh Budaya Rayon Tanjungpinang